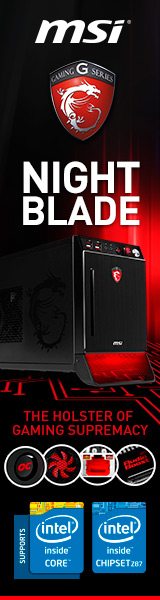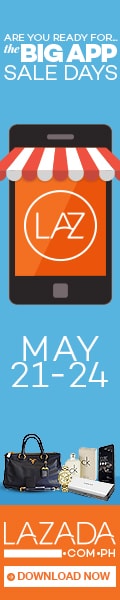Oleh: Lili Suheli
Pengamat Sosial dan Budaya Masyarakat Sekitar
“Tanah adalah ibu. Bila tanah dijual, maka putuslah akar kita sebagai bangsa.”
— Kutipan : Pramoedya Ananta Toer
Medan | Timelinenewsidn.com,- Ketika kita menyusuri desa-desa di Sumatera, Jawa, atau Nusa Tenggara, ada pemandangan yang kian sering terlihat, papan bertuliskan “Dijual” berdiri di pinggir-pinggir kebun, sawah, atau bahkan tanah kosong. Fenomena ini tampak biasa—seolah menjual tanah adalah jalan cepat untuk keluar dari lilitan ekonomi atau memenuhi impian instan: membeli sepeda motor, memperluas rumah, atau sekadar memenuhi gaya hidup konsumtif. Selasa (8/4/2025)
Padahal, ini bukan sekadar transaksi properti. Ini adalah gejala yang mengkhawatirkan—tanda masyarakat mulai melepaskan akar ekonominya sendiri. Dan yang lebih menyedihkan, banyak yang menjual bukan karena perencanaan investasi, melainkan karena ketidaktahuan, tekanan ekonomi, dan ketergantungan pada pola pikir instan.
Tanah, Lebih dari Sekadar Aset. Di dalam konstruksi budaya masyarakat Indonesia, tanah adalah lebih dari sekadar benda. Ia adalah warisan leluhur, sumber penghidupan, dan bagian dari identitas. Dalam kajian antropologi, tanah memiliki nilai simbolik dan spiritual. Tanpa tanah, seseorang dianggap “tak bertanah air” — tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara sosial dan kultural.
Sayangnya, nilai ini semakin tergerus oleh arus modernitas dan kapitalisme. Di tengah ketimpangan ekonomi, tanah menjadi objek spekulasi. Dalam riset Komnas HAM tahun 2023, tercatat lebih dari 3.500 konflik agraria sepanjang satu dekade terakhir, mayoritas karena alih kepemilikan lahan dari masyarakat adat atau petani kecil ke korporasi besar.
Mimpi Instan, Jalan Pintas yang Mahal. Data dari BPS menunjukkan bahwa lebih dari 60% masyarakat perdesaan yang menjual tanahnya tidak memiliki rencana jangka panjang setelahnya. Dalam lima tahun, sebagian besar kembali ke bawah garis kemiskinan karena kehilangan sumber penghidupan tetap.
Tak sedikit pula yang terpaksa menjual lahan karena tergiur iming-iming agen pekerja migran. Mereka berangkat ke luar negeri dengan harapan besar, namun pulang dalam kondisi mengenaskan. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melaporkan, sejak 2019 hingga 2024, lebih dari 1.700 jenazah WNI dikirim dari luar negeri, sebagian besar korban eksploitasi.
Bukankah lebih mulia mengelola sebidang tanah sendiri, meski hasilnya tak secepat gaji di negeri orang, daripada menjadi budak modern di tempat asing?
Belajar dari Negara Tetangga. Kita bisa berkaca pada negara-negara seperti Thailand dan Vietnam. Di sana, pertanian skala kecil dan industri rumahan menjadi tulang punggung ekonomi. Pemerintah mereka tidak hanya memberikan subsidi pupuk atau pelatihan keterampilan, tapi juga melindungi lahan rakyat dari spekulasi dan akumulasi oleh korporasi.
Vietnam, misalnya, berhasil menjaga ketahanan pangannya dengan kebijakan land ceiling—pembatasan kepemilikan tanah untuk mencegah monopoli. Hasilnya, petani tetap punya lahan untuk bertani dan masyarakat tetap bisa mandiri secara ekonomi.
Mengapa Indonesia tidak bisa? Padahal kita memiliki lahan luas, iklim subur, dan penduduk yang pekerja keras.
Negara Harus Hadir, Bukan Absen. Ironisnya, di Indonesia justru terjadi pembiaran sistematis. Oligarki ekonomi menguasai tanah dengan mudah melalui celah hukum, permainan harga, dan lemahnya perlindungan negara terhadap petani dan masyarakat adat.
Badan Bank Tanah yang dibentuk pemerintah justru dikhawatirkan menjadi alat baru untuk mempercepat alih fungsi lahan kepada korporasi. Jika negara tidak mengatur dengan hati-hati, maka akan muncul “penjajahan gaya baru”—bukan oleh bangsa asing, tetapi oleh sesama anak negeri yang menggadaikan kepentingan rakyat demi keuntungan pribadi.
Rumah untuk Hidup, Bukan Sekadar Hunian. Pemerintah sering berdalih membangun rumah susun vertikal karena keterbatasan lahan. Pernyataan ini tidak sepenuhnya benar. Indonesia memiliki lebih dari 1,9 juta km² daratan (BPS 2022), dan hanya sebagian kecil yang digunakan untuk pemukiman. Yang minim bukan lahannya, tetapi keberpihakan dan perencanaan tata ruang.
Rumah ideal bukanlah unit 36 m² di lantai 15, tetapi ruang hidup yang bisa menopang kehidupan keluarga: berkebun, beternak, atau membuat usaha kecil. Tiga rantai tanah sudah cukup untuk membangun kehidupan mandiri. Inilah semangat kedaulatan domestik—sebuah konsep yang harus kembali kita hidupkan.
Tanah Adalah Jati Diri. Menjual tanah tanpa perhitungan adalah menjual masa depan. Saat kita kehilangan tanah, kita kehilangan kedaulatan pangan, kedaulatan ekonomi, dan bahkan kedaulatan berpikir. Generasi mendatang akan menjadi pekerja di atas tanah yang pernah dimiliki leluhurnya. Ini bukan sekadar kehilangan lahan, tetapi kehilangan martabat.
Sebagaimana kata Bung Karno, “Kita harus kembali ke identitas asli kita sebagai bangsa yang bertumpu pada kekuatan sendiri.” Dan kekuatan itu, sesungguhnya, terletak di bawah kaki kita—pada setiap jengkal tanah yang kita miliki dan kelola.
Mari Lindungi Warisan Terakhir. Artikel ini bukan sekadar ajakan idealistik, tapi seruan moral. Kepada masyarakat: kelolalah tanahmu. Jangan menjual hanya karena tergiur keinginan sesaat. Jadikan tanah sebagai basis kekuatan ekonomi keluarga. Kepada pemerintah: hadir dan bertindaklah tegas melindungi lahan rakyat. Jangan hanya berpihak pada korporasi dan pemodal besar.
Karena ketika tanah terakhir dijual, ketika pohon terakhir ditebang, dan ketika sungai terakhir tercemar, barulah kita menyadari bahwa uang tidak bisa dimakan.(Red)